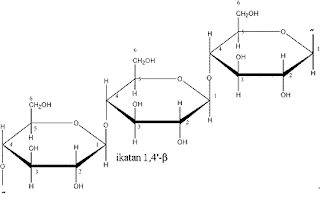|
LAPORAN PRAKTIKUM KIMIA
|
|
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LAJU REAKSI
|
|
Durrotul Maknuna(08), Geta Hidayatun Naimah(13), Hasan Ma’ruf(14), M. Indra Saputra(20), Siti
Aminatus Sa’diyah(27),
Ula Uyun Fuaza(28)
|
A. TUJUAN
Mempelajari
faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi.
B. ALAT DAN BAHAN
1.
Gelas Erlenmenyer 100 ml
2.
Gelas ukur 25 ml
3.
Gelas kimia 100 ml
4.
Tabung reaksi dan rak
5.
Kasa, kaki tiga dan pembakar
spiritus
6.
Thermometer
7.
Pangaduk
8.
Penjepit tabung
9.
Stop watch
10.
Lidi dan korek api
11.
Balon karet
12.
Larutan HCL 0,5 M dan HCL 0,3 M
13.
Batu pualam keping dan serbuk
14.
Larutan H2O2
15.
Larutan H2SO4
0,3 M dan 0,5 M
16.
Larutan Na2S2O3
17.
Serbuk MnO2
18.
Kertas putih dan spidol
C. LANGKAH KERJA
Percobaan 1: Pengaruh Konsentrasi
Terhadap Laju Reaksi
a.
Isilah gelas Erlenmeyer dengan 20
mL larutan HCl 0,3M.
b.
Masukkan 1,5 gr keping pualam ke
dalam balon karet, kemudian pasang dan ikat balon karet itu pada mulut Erlenmeyer
yang berisi larutan HCl. Jaga jangan sampai pualam masuk ke dalam gelas
Erlenmeyer.
c.
Reaksi pualam dalam balon karet
dengan HCl dalam gelas Erlenmeyer dan catat waktu yang diperlukan gas CO2
untuk menegakkan balon karet.
d.
Ulangi langkah a, b, dan c dengan
mengunakan larutan HCl 0,5M. Catat hasilnya pada tabel pengamatan.
Percobaan 2: Pengaruh Konsentrasi
Terhadap Laju Reaksi
a.
Siapkan 1 buah tabung reaksi. Isi
tabung reaksi dengan larutan 10 mL H2SO4 0,3M.
b.
Masukkan sekeping logam seng ke
dalam tabung reaksi.
c.
Dengan menggunakan stopwatch,
catat waktu yang diperlukan untuk reaksi tersebut, yaitu saat logam seng
dimasukkan ke dalam larutan HCl hingga logam seng habis bereaksi.
d.
Ulangi langkah a, b, dan c untuk
larutan H2SO4 0,5M.
Percobaan 3: Pengaruh Suhu
Terhadap Laju Reaksi
a.
Buat tanda silang dengan spidol
di atas kertas putih.
b.
Isi Elenmeyer dengan 10 mL
larutan HCl 0,3M, kemudian latekkan di atas tanda silang.
c.
Tuang 10 mL larutan Na2
S2O3 ke dalam Erlenmeyer berisi HCl 0,3M.
d.
Catat waktu yang diperlukan untuk
reaksi mulai dari penuangan hingga tanda silang tidak terlihat.
e.
Ulangi langkah b-d tetapi
panaskan terlebih dahulu larutan Na2 S2O3
sebelum dicampur dengan HCl sampai suhu
.
Percobaan 4: Pengaruh Suhu
Terhadap Laju Reaksi
a.
Masukkan 10 mL larutan H2O2
ke dalam tabung reaksi.
b.
Letakkan lidi membara diatas
tabung reaksi.
c.
Amati perubahan yang terjadi pada
bara lidi.
d.
Tambahkan 0,5 gr MnO2
ke dalam larutan H2O2.
e.
Letakkan lidi membara di atas
tabung reaksi dan amati perubahan pada bara lidi. Catat hasil pengamatan anda.
D. DASAR TEORI
Reaksi kimia adalah proses berubahnya pereaksi
menjadi hasil reaksi. Proses itu ada yang cepat dan ada yang lambat, contohnya
bensin terbakar lebih cepat disbanding dengan minyak tanah. Ada reaksi yang berlangsung
sangat cepat, seperti membakar dinamit yang menghasilkan ledakan, dan ada yang
sangat lambat seperti perkaratan besi. Dalam hal ini dikemukakakan cara
menentukan laju reaksibdan factor factor yang mempengaruhinya.
Faktor-faktor yang mempenguruhi laju
reaksi yang dikenal adalah sebagai berikut :
1. Sifat
pereaksi
Salah satu factor penentu laju reaksi adalah sifat
pereaksi, ada yang reaktif dan ada juga yang kurang reaktif, misalnya bensin
lebih cepata terbakar daripada minyak tanah. Demikian juga logam natrium
bereaksi cepat dengan air, sedangkan logam magnesium lambat.
2. Konsentrasi
pereaksi
Dua molekul yang akan bereaksi harus bertabrakan
langsung. Jiak konsentrasi pereaksi diperbesar, berarti kerapatannya bertambah
dan memperbanyak kemungkinan tabrakan sehingga akan mempercepat reksi. Akan
tetapi harus diingat behwa tidak selalu pertambahan konsentrasi pereaksi
meningkatkan laju reaksi, karena laju reaksi dipengaruhi oleh factor factor
lain.
3. Suhu
Hampir semua reaksi menjadi lebih cepat bila suhu
dinaikkan, karena kalor yang diberikan akan menambah energy kinetic partikel
pereaksi. Akibatnya, jumlah dan energy tabrakan bertambah besar.
4. Katalis
Laju suatu reaksi dapat diubah (umunya dipercepat)
dengan menambahkan zat yang disebut katalis. Katalis sangat diperlukan dalam
reaksi zat organic termasuk dalam organism. Katalis dalam organism disebut
enzim dan dapat mempercepat reaksi ratusan sampai puluhan ribu kali.
E. DATA HASIL PENGAMATAN
|
No.
|
Pelarut
|
Larutan
|
Waktu
|
Δt
|
|
Percobaan 1
|
20 mL HCl 0,3M
|
1,5 gr keping pualam
|
1’03”
|
51”
|
|
|
20 mL HCl 0,5M
|
1,5 gr keping pualam
|
12”
|
|
|
Percobaan 2
|
10 mL H2SO4 0,3M
|
1 keping logam seng
|
3’55”
|
8”
|
|
|
10 mL H2SO4 0,5M
|
1 keping logam seng
|
3’47”
|
|
|
Percobaan 3
|
10 mL HCl 0,3M
|
10 mL Na2 S2O3
|
8’42”
|
5’02”
|
|
|
10 mL HCl 0,3M
|
10 mL Na2 S2O3
|
3’40”
|
|
|
Percobaan 4
|
10 mL H2O2
|
0,5 gr MnO2
|
-
|
-
|
F. ANALISIS DATA
Percobaan 1
Semakin besar konsentrasi HCl maka laju reaksinya
semakin cepat. HCl 0,3M menempuh waktu 1’03” untuk mengembangkan balon karet, sedangkan
HCl 0,5M menempuh waktu hanya 12”. Perbedaannya yaitu 51”. Hal ini karena balon
karet terisi oleh CO2 hasil dari reaksi asam klorida(HCl) dengan
batu pualam(CaCO3).
HCl(aq) + CaCO3(s) à CaCl2(s) + H2O(l) +
CO2(g)
Percobaan 2
Melihat data hasil
percobaan yang telah peneliti lakukan pada percobaan kedua. Yang mana
menggunakan asam sulfat (H2SO4) 0,3M bercampur dengan
sekeping logam seng(Zn) yang dimasukkan kedalam tabung reaksi, ternyata
membutuhkan waktu 3’55”. Hal ini menunjukkan reaksi akan berlangsung lebih
cepat jika konsentrasi pereaksi diperbesar, karena zat yang konsentrasinya
besar mengandung jumlah partikel yang lebih banyak, sehingga partikelnya
tersusun lebih rapat dibanding zat yang konsentrasinya rendah. Hal ini telah
ditunjukkan pada percobaan kedua yakni pada 10 mL H2SO4 0,5M
yang konsentrasinya lebih tinggi membutuhkan waktu yang lebih cepat dari
percobaan yang pertama.
Zn + H₂SO₄ → ZnSO₄ + H₂
Percobaan 3
Pada
Percobaan 3 larutan HCl 0,1M
direaksikan dengan larutan Na2S2O3 pada suhu
yang berbeda yaitu pada suhu normal
ruangan dan dipanaskan menjadi
. Waktu reaksi dicatat sampai terbentuk endapan
belerang didalam tabung erlemenyer.Persamaan
reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut:
Na2S2O3(aq)
+ HCl(aq)→ 2NaCl(aq) + H2O(l) + SO2(g)
+ S(s)
Berdasarkan
tabel terlihat bahwa semakin
besar temperatur semakin cepat endapan terbentuk dan dari data percobaan pada tabel dapat dilihat bahwa semakin
besar temperature, maka waktu yang diperlukan untuk mereaksikan antara HCl dan
Na2S2O3 semakin kecil, berarti laju reaksi
semakin cepat. Dengan demikian semakin
tinggi temperatur pereaksi, semakin
cepat laju reaksinya.
Percobaan 4
Pada
tabung reaksi direaksikan antara larutan hidrogen peroksida (H2O2)
dan
pirolusit (MnO2). Setelah MnO2 disatukan dengan H2O2 terjadi reaksi sepontan.
MnO2 + 2H2O2 -->
MnO2 + O2 + 2H2O
Pada
reaksi ini terlihat adanya sedikit gelembung dan warna dari campuran abu kehitaman. Suhunya meningakat drastis dan keluar asap abu-abu
diatasnya. Ketika peneliti memasukkan bara lidi kedalam tabung reaksi,
muncullah api didalam tabung reaksi tapi tak berlangsung lama. Api ini
terbentuk karena uap dan oksigen dari reaksi yang tersebut. Menurut peneliti
hal ini terjadi karena MnO2 adalah termasuk katalis.
Berbeda saat H2O2 tidak di satukan
dengan MnO2, bara lidi yang dimasukkan kedalam tabung reaksi itu
akan semakin padam. Api tidak bisa menyala. Menurut peneliti hal ini
dikarenakan larutan H2O2 merupakan larutan basa.
G. KESIMPULAN
Dari semua percobaan yang
peneliti lakukan membuktikan bahwa konsentrasi dan suhu mempengaruhi terhadap
laju reaksi. Jika konsentrasi naik maka laju reaksi juga naik, begitu juga jika
suhu naik maka laju reaksi juga naik dan juga sebaliknya.
Persamaan laju
reaksi didefinisikan dalam bentuk konsentrsi reaktan maka dengan naiknya konsentrasi
maka naik pula kecepatan reaksinya. Artinya semakin tinggi konsentrasi maka
semakin banyak molekul reaktan yang tersedia dengan demikian kemungkinan
bertumbukan akan semakin banyak juga sehingga kecepatan reaksi meningkat. Jadi semakin
tinggi konsentrasi, semakin cepat pula laju reaksinya
Suhu juga turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi.
Apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung
dinaikkan, maka menyebabkan partikel
semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering, menyebabkan laju reaksi
semakin besar. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka partikel semakin tak
aktif, sehingga laju reaksi semakin kecil.
I. DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Hiskia . 2001. ELEKTROKIMIA dan KINETIKA
KIMIA. Bandung ; Citra Aditya bakti.
Purba,
Michael.2006.Kimia untnk SMA Kelas XI. Jakarta: Erlangga.